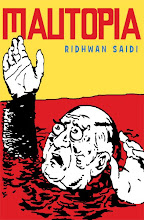Masa saya tonton ini filem, entah bagaimana imaginasi saya telah bawa saya mengembara jauh ke masa depan. Dengan lebih tepat, 100 tahun akan datang yakni 2109 a.d. bersamaan 1530 hijrah. Kononnya apa yang saya tonton itu – jika tiada malapetaka-lah – imej-imej kota Kuala Lumpur 100 tahun dulu. Jika mentaliti pembesar-pembesar kita ini masih sama macam dulu (sekarang,) tidak mustahil, nanti, ruang-ruang yang dipaparkan seperti Coliseum, Central Market & pasar malam akan pupus. Tambah aneh, KLCC kita mungkin akan terpinggir akibat senibina-senibina menara kontemporari – rekaan arkitek luar – yang jauh lebih baru dan canggih (macam Masjid Negara dengan Masjid Putrajaya; ini pun baru lebih kurang 50 tahun beza.)
Bagi saya filem ini seolah dekat dengan filem Punggok Rindukan Bulan (yang belum saya tonton,) bukan dari segi cerita, tapi macam satu bentuk tanggungjawab sosial dalam mendokumenkan bangunan lama, dan dalam kes ini, manusia dan senibina kota Kuala Lumpur. Mana tahu jika 100 tahun akan datang – jika revolusi masih terbantut – kelahiran semula ala Fahmi Reza boleh jadikan filem ini sebagai salah satu stock footage ataupun rujukan berkenaan 98.
Seperkara yang menarik tentang filem ini, selain tindak tanduk natural (walaupun ada yang dibuat) masyarakat berbahasa Tamil, mainan kata-kata serta imej-imej yang cantik, muncul simbol-simbol atau logo-logo bagi setiap institusi atau syarikat seperti Utusan, Youtube, TV3 dan lain-lain. Logo-logo ini, tanpa kita sedari sebenarnya telah membentuk acuan 'rasa percaya' orang-orang kita, oleh itu – ‘Dewata Malaysia’. Hishamuddin Rais yang mengaku non-governmental individualist itu, pernah tulis yang orang kita bertuhankan kereta dan jalanraya. Ini saya ‘percaya’, tapi pabila mereka-mereka ini keluar daripada kereta, lain pula ceritanya. Mereka taksub dengan kepercayaan logo masing-masing, cewah macam polytheist pula. Jika tak percaya KFC, percaya kepada McDonald’s. Jika tak percaya TGV, percaya kepada GSC. Jika tak percaya Carrefour, percaya kepada Tesco. Dan pabila mereka percaya, maka mereka beli:
“I believe, therefore I buy-lah.”
Ini bagaimanapun hanya tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat bahawasanya ia logo-logo kompeni konglomerat korporat keparat global mahupun lokal. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi bentuk-bentuk dewata logo yang lain seperti Ares (polis dewa) dan Zeus (raja dewa.)
Akhir kata, jika Yasmin Ahmad ada ‘ingatkan’ kita tentang perbezaan najis dan haram, Melayu dan Malaysia, Islam dan Melayu dan lain-lain isu agama & warna kulit mungkin (saya hanya pernah tonton Sepet dan Gubra.) Melalui filem ini, Amir Muhammad tanpa disedari (atau sedar?) telah ‘ingatkan’ kita tentang beza Tamil dan India. Jangan bohong, sebab ada di antara kita yang anggap Tamil itu bangsa walhal Tamil itu bahasa. Sebab itu kadang-kadang saya pelik jika ada (memang ada!) orang yang mempersoalkan soal kaum dalam filem Malaysian Gods (2008) yang berbahasa Tamil ini (ironinya mereka berbahasa Inggeris sedangkan mereka 'kaum' Melayu.) Apa cerit?
Ridhwan Saidi
![]3 | |\| /= | |_ [- |\/|](http://3.bp.blogspot.com/-STivabIH0iU/Tl-ERf_spWI/AAAAAAAABbg/OPMk93q8lc0/s1600/BF2011c.gif)