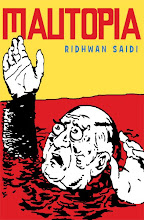Catatan tahun 2009 mendapati terdapat 1,468,984 orang warga yang menetap di sekitar Kuala Lumpur. Itu tak dikira dengan para buruh import yang jumlahnya semakin bertambah dari semasa ke semasa. Saya yakin jumlahnya lebih besar bila semuanya dicampur kira. Kepadatan melampau ini pasti menimbulkan masalah petempatan penduduk. Rumah adalah sebahagian dari hak asasi manusia. Namun persoalannnya adakah rumah-rumah yang disediakan mampu menampung limpahan penghuni kota?
Ekspresi pembandaran yang kita pakai di negara ini merupakan ekspresi budaya kapitalisme. Dalam pembandaran seumpama ini, kehidupan manusia telah dikotak-kotakkan dalam sistem pembandaran yang rigid, di mana manusia secara tanpa sedar telah menghadkan pergerakan mereka sendiri. Manusia hari ini juga lebih banyak menghabiskan masanya untuk terperap di dalam bilik, sama ada melayan internet, bermain permainan video, menonton televisyen, mendengar radio, dll – ah, serupa saja dengan makhluk yang menulis.
Sebetulnya, saya ingin melanjutkan bicara saya tentang ruang awam. Demi menampung limpahan penghuni kota, kita wajar memikirkan cara terbaik menangani krisis ini. Antaranya ialah, kita wajar menghidupkan semula potensi ruang awam dengan mengubah sikap prejudis terhadap pengguna ruang ini. Kehidupan moden kapitalisme yang keras seperti terkepung dalam bongkah-bongkah konkrit pejal perlu dicairkan dengan merayakan ruang awam.
Ketika Amerika Syarikat dilanda “the Great Depression” pada awal abad ke-20, munculnya golongan penghuni kota yang tidak berumah, yang terdiri dari para drifters, vagabond, tramps, bums, hobos. Mereka ini sisa-sisa kejatuhan kapitalisme pada waktu itu. Dan kini, tradisi ini masih lagi berlangsung di mana-mana bandar di serata dunia. Dalam keterdesakan mencari tempat tinggal pada hari ini, memilih untuk menjadi salah satu dari golongan yang saya nyatakan di atas perlu diterima sebagai satu alternatif. Praktis ini mungkin tak sesuai untuk yang sudah berkeluarga, tapi untuk mereka yang bujang, kehidupan fleksibel neo-nomadisme ini mungkin keputusan yang paling tepat.
Masalahnya, masyarakat awam secara amnya sering bersikap prejudis dengan golongan yang dikatakan ‘merempat’ ini. Masyarakat umumnya gagal menghargai golongan ini sebagai sebahagian ahli masyarakat yang “valid.” Golongan ini malah dipinggir dan dituduh sebagai ‘orang asing’, hanya semata-mata mereka tidak berumah. Tapi ramai di kalangan kita tak sedar mereka sedang merayakan potensi ruang awam secara tepat. Adakah mereka sengaja memilih untuk tidak memiliki rumah, seperti mana orang ‘normal’ yang lain? Mungkin ya, mungkin tidak.
Saya pernah melihat di KL terdapat segelintir warga kota yang tingggal di bawah jejambat. Ruang di bawah jejambat ini dimaksimumkan potensinya sebagai tempat berteduh. Ruang itu dijadikan seolah-olah rumah yang tetap, lengkap dengan set sofa terpakai, gerobok lama, tempat menyidai pakaian dan dapur. Sebagai seorang pemerhati seni bina dan urban yang poser, saya mendapati tindakan golongan ini sebagai satu tindakan yang radikal. Mereka juga lebih wajar dianggap sebagai kelompok environmentalist yang sebenar. Saya sama sekali tak akan menganggap kelompok ini sebagai sebahagian dari ahli masyarakat yang patut disingkirkan. Dalam kesempitan ruang kota yang mencengkam, sudah tiba masanya masyarakat menerima kewujudan golongan ini seadanya tanpa diiringi rasa prejudis.
Tapi yang lebih fleksibel saya kira adalah dari kalangan vagabond/drifters/flâneur. Kelompok ini telah meneroka potensi ruang awam secara berani dan spontan. Mereka ‘menceroboh’ ke mana sahaja ruang-ruang yang boleh dicerobohi. Cuma dengan sedikit kekangan akibat aturan bandar kapitalis moden, ‘pencerobohan’ golongan ini pasti lebih mencabar dan beresiko. Sebab itu saya amat percaya bahawa bandar masa depan yang ideal hanya bermakna sekiranya manusia dapat menyediakan lebih banyak ruang-ruang awam untuk dimaksimumkan penggunaannya.
Jika diperhatikan terdapat beberapa ruang awam yang telah dimonopoli oleh para buruh import di sekitar KL, seperti di kawasan berhampiran Plaza Kotaraya dan Hentian Puduraya. Setiap hujung minggu, para buruh ini akan mengambil kesempatan percutian kerja mereka untuk berkumpul dan bersantai dengan selamba di tengah-tengah kawasan lapang tersebut. Saya percaya, ramai orang tempatan yang tidak menyukai permandangan sebegini. Selalunya dikatakan ‘mencemari imej bandaraya.’ Namun bagi saya, adalah sangat ironi kerana golongan imigran ini pada hakikatnya sedang mempraktiskan ruang urban dalam erti kata sebenar. Mereka telah memaksimumkan potensi ruang itu dengan ekspresi spontan; duduk bersila sambil berborak-borak secara berkumpulan dengan beberapa botol Coke dan Thai Song sebagai penghilang dahaga tanpa menghiraukan orang sekeliling. Fenomena ini barangkali adalah letusan ekspresi spontan yang terhasil dari kehidupan harian para buruh ini yang tinggal berasak-asak dalam rumah sewa yang sempit, boleh jadi satu rumah dikongsi hingga 15 orang. Tapi sangat berbeza dengan orang tempatan yang segan dengan matahari lalu menyorok di dalam gedung-gedung membeli-belah berhawa dingin di hujung minggu.
Selain itu, orang awam sewajarnya berpeluang menggunakan kawasan lapang seperti di Dataran Merdeka secara bebas. Biar kena dengan namanya: DATARAN MERDEKA. Kawasan lapang yang berpadang rumput berpotensi menjadi pusat persinggahan para “backpackers” dari dalam dan luar negara. Sesiapa saja terutama puak vagabond/drifters/etc juga berpeluang menakluki kawasan ini. Kawasan berpadang rumput ini perlu dimerdekakan menjadi ruang sosial di mana sesiapa saja bebas mendirikan pertempatan sementara seperti khemah. Perkhemahan ini jika dilangsungkan secara spontan pasti menarik, saya rasa. Ia respon terhadap gaya hidup kontemporari dan masa depan: neo-nomadisme! Sedangkan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Paris, terdapat penghuni kota metropolis tersebut yang telah tinggal dalam ‘rumah kotak’ akibat dari kepayahan mencari bilik/rumah sewa dengan kadar bayaran yang termampu. Di sini, perlu difahami bahawa ‘rumah kotak’ itu hanyalah permulaan sebelum ianya berevolusi menjadi “mobile-housing.” Sebab itu tak mustahil andainya akan datang konsep “mobile-housing” diterima umum.
Sesetengah ruang awam juga wajar dibebaskan dari notion kawasan perkumpulan para pelancong. Sebaliknya, pelancong-lah yang sepatutnya bersebati dengan ‘genius loci’ (semangat setempat) di kawasan terbabit. Kawasan poser seperti “Arab Square” di Bukit Bintang tak patut wujud! Warga tempatan pula tak perlu berpura-pura ‘sopan’ di depan pelancong asing, sebaliknya sentiasa menampilkan citra hidup mereka yang sebenar. Lagi satu hal, idea merayau di siang hari lebih selamat dari di malam hari perlu ditolak.
Potensi ruang awam juga hanya dapat dimaksimumkan dengan meminimumkan secara maksimum penggunaan ground level bagi mendirikan bangunan. Biarkan ruang aras tanah ditakluk oleh pergerakan publik secara maksimum. Kontur dan topografi aras tanah yang original wajib dipelihara bagi menimbulkan kesan pergerakan yang lebih mencabar dan organik. Jumlah plot ratio wajar dikecilkan. Mungkin sesebuah bangunan yang ingin didirikan di kawasan bandar terutama bangunan persendirian hanya dibenar menggunakan 20-30 peratus daripada seluruh keluasan tapak. Maka bangunan perlu dibangunkan dengan menggunakan konsep “on-stilt” atau “pilotis.” Seterusnya lebihan ruang aras tanah ini secara automatik wajib diiktiraf sebagai ruang awam yang boleh di-exercise oleh sesiapa saja.
Dengan luasnya ruang aras tanah ini, bukan saja memudahkan pergerakan pejalan kaki, malah ia menghidupkan peluang interaksi sosial antara masyarakat. Interaksi sosial yang terhasil juga tak tertakluk di kalangan kelompok yang saling mengenali, tetapi potensinya ialah semua orang lebih berpeluang untuk berinteraksi kerana ruang tidak lagi dibatasi oleh blok-blok bangunan. Bahkan konsep bandar sebegini memungkinkan pelbagai lagi aktiviti kehidupan dijalankan, tak terhad kepada aktiviti komersial semata-mata. Misalnya aktiviti sukan futsal, sukaneka, kenduri kahwin, pidato umum, persembahan muzik, teater, tayangan filem, art installation, pameran terbuka, dll yang dilakukan secara spontan dan percuma. Pendek kata, kehidupan bagaikan merayakan sebuah pesta. Di samping itu, ia turut mampu mengurangkan kadar jenayah kerana ruang menjadi lebih terbuka. Ruang yang lebih terbuka pasti menjanjikan satu bentuk budaya yang lebih menarik.
Kehidupan masa kini dan masa hadapan perlu kembali merayakan potensi ruang sosial yang bebas. Jika pada zaman dahulu kala, manusia bebas bertebaran secara anarki ke mana saja, tapi kini kapitalisme membatasi pergerakan manusia dengan sempadan negara-bangsa, yang juga menyebabkan ruang dan masa kehidupan lebih banyak terperap di dalam rumah atau pejabat ataupun kilang. Maka di kemuncak kapitalisme hari ini ruang sosial kehidupan itu perlu dibuka kembali dengan merayakan neo-nomadisme, yang semestinya mencari peluang bermain-main di luar kepungan rumah, pejabat mahupun kilang. "Just come out and play, my friend!"
Mohd Ikhwan Abu Bakar
Ekspresi pembandaran yang kita pakai di negara ini merupakan ekspresi budaya kapitalisme. Dalam pembandaran seumpama ini, kehidupan manusia telah dikotak-kotakkan dalam sistem pembandaran yang rigid, di mana manusia secara tanpa sedar telah menghadkan pergerakan mereka sendiri. Manusia hari ini juga lebih banyak menghabiskan masanya untuk terperap di dalam bilik, sama ada melayan internet, bermain permainan video, menonton televisyen, mendengar radio, dll – ah, serupa saja dengan makhluk yang menulis.
Sebetulnya, saya ingin melanjutkan bicara saya tentang ruang awam. Demi menampung limpahan penghuni kota, kita wajar memikirkan cara terbaik menangani krisis ini. Antaranya ialah, kita wajar menghidupkan semula potensi ruang awam dengan mengubah sikap prejudis terhadap pengguna ruang ini. Kehidupan moden kapitalisme yang keras seperti terkepung dalam bongkah-bongkah konkrit pejal perlu dicairkan dengan merayakan ruang awam.
Ketika Amerika Syarikat dilanda “the Great Depression” pada awal abad ke-20, munculnya golongan penghuni kota yang tidak berumah, yang terdiri dari para drifters, vagabond, tramps, bums, hobos. Mereka ini sisa-sisa kejatuhan kapitalisme pada waktu itu. Dan kini, tradisi ini masih lagi berlangsung di mana-mana bandar di serata dunia. Dalam keterdesakan mencari tempat tinggal pada hari ini, memilih untuk menjadi salah satu dari golongan yang saya nyatakan di atas perlu diterima sebagai satu alternatif. Praktis ini mungkin tak sesuai untuk yang sudah berkeluarga, tapi untuk mereka yang bujang, kehidupan fleksibel neo-nomadisme ini mungkin keputusan yang paling tepat.
Masalahnya, masyarakat awam secara amnya sering bersikap prejudis dengan golongan yang dikatakan ‘merempat’ ini. Masyarakat umumnya gagal menghargai golongan ini sebagai sebahagian ahli masyarakat yang “valid.” Golongan ini malah dipinggir dan dituduh sebagai ‘orang asing’, hanya semata-mata mereka tidak berumah. Tapi ramai di kalangan kita tak sedar mereka sedang merayakan potensi ruang awam secara tepat. Adakah mereka sengaja memilih untuk tidak memiliki rumah, seperti mana orang ‘normal’ yang lain? Mungkin ya, mungkin tidak.
Saya pernah melihat di KL terdapat segelintir warga kota yang tingggal di bawah jejambat. Ruang di bawah jejambat ini dimaksimumkan potensinya sebagai tempat berteduh. Ruang itu dijadikan seolah-olah rumah yang tetap, lengkap dengan set sofa terpakai, gerobok lama, tempat menyidai pakaian dan dapur. Sebagai seorang pemerhati seni bina dan urban yang poser, saya mendapati tindakan golongan ini sebagai satu tindakan yang radikal. Mereka juga lebih wajar dianggap sebagai kelompok environmentalist yang sebenar. Saya sama sekali tak akan menganggap kelompok ini sebagai sebahagian dari ahli masyarakat yang patut disingkirkan. Dalam kesempitan ruang kota yang mencengkam, sudah tiba masanya masyarakat menerima kewujudan golongan ini seadanya tanpa diiringi rasa prejudis.
Tapi yang lebih fleksibel saya kira adalah dari kalangan vagabond/drifters/flâneur. Kelompok ini telah meneroka potensi ruang awam secara berani dan spontan. Mereka ‘menceroboh’ ke mana sahaja ruang-ruang yang boleh dicerobohi. Cuma dengan sedikit kekangan akibat aturan bandar kapitalis moden, ‘pencerobohan’ golongan ini pasti lebih mencabar dan beresiko. Sebab itu saya amat percaya bahawa bandar masa depan yang ideal hanya bermakna sekiranya manusia dapat menyediakan lebih banyak ruang-ruang awam untuk dimaksimumkan penggunaannya.
Jika diperhatikan terdapat beberapa ruang awam yang telah dimonopoli oleh para buruh import di sekitar KL, seperti di kawasan berhampiran Plaza Kotaraya dan Hentian Puduraya. Setiap hujung minggu, para buruh ini akan mengambil kesempatan percutian kerja mereka untuk berkumpul dan bersantai dengan selamba di tengah-tengah kawasan lapang tersebut. Saya percaya, ramai orang tempatan yang tidak menyukai permandangan sebegini. Selalunya dikatakan ‘mencemari imej bandaraya.’ Namun bagi saya, adalah sangat ironi kerana golongan imigran ini pada hakikatnya sedang mempraktiskan ruang urban dalam erti kata sebenar. Mereka telah memaksimumkan potensi ruang itu dengan ekspresi spontan; duduk bersila sambil berborak-borak secara berkumpulan dengan beberapa botol Coke dan Thai Song sebagai penghilang dahaga tanpa menghiraukan orang sekeliling. Fenomena ini barangkali adalah letusan ekspresi spontan yang terhasil dari kehidupan harian para buruh ini yang tinggal berasak-asak dalam rumah sewa yang sempit, boleh jadi satu rumah dikongsi hingga 15 orang. Tapi sangat berbeza dengan orang tempatan yang segan dengan matahari lalu menyorok di dalam gedung-gedung membeli-belah berhawa dingin di hujung minggu.
Selain itu, orang awam sewajarnya berpeluang menggunakan kawasan lapang seperti di Dataran Merdeka secara bebas. Biar kena dengan namanya: DATARAN MERDEKA. Kawasan lapang yang berpadang rumput berpotensi menjadi pusat persinggahan para “backpackers” dari dalam dan luar negara. Sesiapa saja terutama puak vagabond/drifters/etc juga berpeluang menakluki kawasan ini. Kawasan berpadang rumput ini perlu dimerdekakan menjadi ruang sosial di mana sesiapa saja bebas mendirikan pertempatan sementara seperti khemah. Perkhemahan ini jika dilangsungkan secara spontan pasti menarik, saya rasa. Ia respon terhadap gaya hidup kontemporari dan masa depan: neo-nomadisme! Sedangkan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Paris, terdapat penghuni kota metropolis tersebut yang telah tinggal dalam ‘rumah kotak’ akibat dari kepayahan mencari bilik/rumah sewa dengan kadar bayaran yang termampu. Di sini, perlu difahami bahawa ‘rumah kotak’ itu hanyalah permulaan sebelum ianya berevolusi menjadi “mobile-housing.” Sebab itu tak mustahil andainya akan datang konsep “mobile-housing” diterima umum.
Sesetengah ruang awam juga wajar dibebaskan dari notion kawasan perkumpulan para pelancong. Sebaliknya, pelancong-lah yang sepatutnya bersebati dengan ‘genius loci’ (semangat setempat) di kawasan terbabit. Kawasan poser seperti “Arab Square” di Bukit Bintang tak patut wujud! Warga tempatan pula tak perlu berpura-pura ‘sopan’ di depan pelancong asing, sebaliknya sentiasa menampilkan citra hidup mereka yang sebenar. Lagi satu hal, idea merayau di siang hari lebih selamat dari di malam hari perlu ditolak.
Potensi ruang awam juga hanya dapat dimaksimumkan dengan meminimumkan secara maksimum penggunaan ground level bagi mendirikan bangunan. Biarkan ruang aras tanah ditakluk oleh pergerakan publik secara maksimum. Kontur dan topografi aras tanah yang original wajib dipelihara bagi menimbulkan kesan pergerakan yang lebih mencabar dan organik. Jumlah plot ratio wajar dikecilkan. Mungkin sesebuah bangunan yang ingin didirikan di kawasan bandar terutama bangunan persendirian hanya dibenar menggunakan 20-30 peratus daripada seluruh keluasan tapak. Maka bangunan perlu dibangunkan dengan menggunakan konsep “on-stilt” atau “pilotis.” Seterusnya lebihan ruang aras tanah ini secara automatik wajib diiktiraf sebagai ruang awam yang boleh di-exercise oleh sesiapa saja.
Dengan luasnya ruang aras tanah ini, bukan saja memudahkan pergerakan pejalan kaki, malah ia menghidupkan peluang interaksi sosial antara masyarakat. Interaksi sosial yang terhasil juga tak tertakluk di kalangan kelompok yang saling mengenali, tetapi potensinya ialah semua orang lebih berpeluang untuk berinteraksi kerana ruang tidak lagi dibatasi oleh blok-blok bangunan. Bahkan konsep bandar sebegini memungkinkan pelbagai lagi aktiviti kehidupan dijalankan, tak terhad kepada aktiviti komersial semata-mata. Misalnya aktiviti sukan futsal, sukaneka, kenduri kahwin, pidato umum, persembahan muzik, teater, tayangan filem, art installation, pameran terbuka, dll yang dilakukan secara spontan dan percuma. Pendek kata, kehidupan bagaikan merayakan sebuah pesta. Di samping itu, ia turut mampu mengurangkan kadar jenayah kerana ruang menjadi lebih terbuka. Ruang yang lebih terbuka pasti menjanjikan satu bentuk budaya yang lebih menarik.
Kehidupan masa kini dan masa hadapan perlu kembali merayakan potensi ruang sosial yang bebas. Jika pada zaman dahulu kala, manusia bebas bertebaran secara anarki ke mana saja, tapi kini kapitalisme membatasi pergerakan manusia dengan sempadan negara-bangsa, yang juga menyebabkan ruang dan masa kehidupan lebih banyak terperap di dalam rumah atau pejabat ataupun kilang. Maka di kemuncak kapitalisme hari ini ruang sosial kehidupan itu perlu dibuka kembali dengan merayakan neo-nomadisme, yang semestinya mencari peluang bermain-main di luar kepungan rumah, pejabat mahupun kilang. "Just come out and play, my friend!"
Mohd Ikhwan Abu Bakar
![]3 | |\| /= | |_ [- |\/|](http://3.bp.blogspot.com/-STivabIH0iU/Tl-ERf_spWI/AAAAAAAABbg/OPMk93q8lc0/s1600/BF2011c.gif)